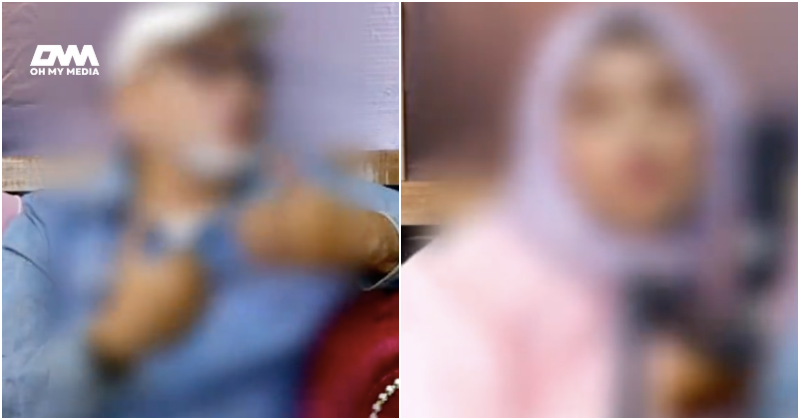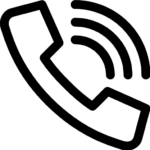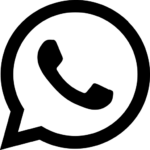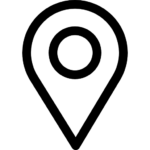Apakah Toleransi Ada Batasnya? – Islami[dot]co
![Apakah Toleransi Ada Batasnya? – Islami[dot]co Apakah Toleransi Ada Batasnya? – Islami[dot]co](https://islami.co/wp-content/uploads/2019/01/berbagi-film-pendek-penggugah-toleransi-yang-mengharukan.jpg)
Saat ini sebagian orang, juga kelompok, menginginkan agar kebebasan berkespresi itu ditoleransi atau dibolehkan di negara Indonesia. Dengan mengatasnamakan hak asasi, semua kegiatan, ekspresi, maupun bentuk tindakan lainnya diberi hak oleh negara.
Ada satu pertanyaan yang muncul, apakah negara maupun warga negara harus mentolerir semua bentuk ekspresi kebebasan tersebut? Dengan mengatasnamakan kebebasan dan kesetaraan, apakah semua tindakan itu perlu ditoleransi? Atau dengan pertanyaan lain, toleransi itu ada batasnya apa nggak sih?
Reiner Forst (2013) pernah mengatakan hal menarik yaitu tentang batas-batas toleransi. Batasan ini penting untuk kita ketahui supaya tidak kebablasan dalam memahami atau mempraktikkan toleransi baik untuk interaksi kita kepada sesama umat beragama, maupun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.
Misalnya, apakah kita akan bersikap toleran terhadap kelompok orang yang melakukan aksi kekerasan berbasis agama meski satu akidah. Atau contoh lainnya, apakah kita tetap toleran melihat orang-orang di sekeliling kita ada yang melakukan sex bebas, perjudian, mabuk-mabukan, dan tindakan lainnya.
Di sini, Reiner Forst sebenarnya tidak memiliki konsepsi yang jelas tentang batasan toleransi di atas. Ini disebabkan karena masing-masing bangsa memiliki historisitas berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda, dan memiliki kebudayaan yang berbeda.
Oleh karena itu, batasan toleransinya berdasarkan kebudayaan itu sendiri baik yang dikonstruksi melalui interaksi manusianya, maupun dari agama.
Bagi Forst, bisa jadi suatu tindakan yang bersifat patologi di negara A tidak dinilai sebagai patologi di negara B. Bisa jadi fenomena sex bebas, gay, lesbi, minum alkohol, diperbolehkan di negara lain, sementara di negara lainnya tidak memperbolehkan.
Misalnya lagi, ada negara yang membolehkan peredaran minuman beralkohol namun hanya sebatas sekian. Semua ini tergantung bangsa atau negara tersebut dalam menegosiasikan batas toleransinya.
Apakah itu semua penting. Bukankah itu semua adalah bentuk kebebasan kita sebagai manusia. Jika pertanyaan seperti ini yang muncul, kembali lagi ke tujuan awal adanya negara dan mungkin juga diturunkannya agama. Keberadaan kedua institusi tersebut pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol, mengendalikan, dan menilai baik buruknya tindakan manusia. Semua ini ada untuk keteraturan sosial.
Namun jangan disalahartikan bahwa keduanya bisa bergabung. Agama dan negara itu berbeda, kendatipun keduanya masih saling bisa mengisi dan melengkapi.
Keduanya juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sesekuler apapun negara pasti membutuhkan agama. Bapak positivisme, Auguste Comte, yang dikenal bapak sekulernya masyarakat modern pun membentuk agama baru yaitu agama humanisme. Dalam agama humanisme, Comte memiliki ajaran, aturan, dan etika yang ditawarkan pada masyarakat positivistik.
Jadi jangan memahami agama secara sempit. Agama memiliki makna yang luas. Agama menyangkut pada persoalan keyakinan seseorang atas sesuatu. Itu yang disebut agama. Konsekuensinya, orang tersebut akan melakukan apapun untuk menunjang keyakinannya.
Saya ambil contoh, ketika orang sudah fanatik terhadap bola, ia akan berusaha melihatnya secara langsung di lapangan, atau minimal nobar, dimanapun klub mereka bermain. Ini juga disebut ‘agama’.
Dengan demikian, mereka juga terikat dengan aturan yang ada di klub tersebut. Dan, masing-masing klub memiliki aturan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing suporter akan terikat dengan aturan di setiap klub yang dibelanya.
Kembali lagi ke persoalan batasan toleransi. Batasan toleransi mestinya dikembalikan ke bangsa masing-masing. Jika suatu tindakan itu memang menjadi budaya di negara tersebut, maka tindakan itu bisa jadi hanya boleh di bangsa itu sendiri dan tidak cocok untuk negara lainnya.
Contoh yang paling konkrit dan masih hangat adalah gelaran piala dunia 2022. Qatar sebagai tuan rumah melarang adanya aktivitas LGBT. Berbagai negara peserta piala dunia banyak yang memprotesnya, salah satunya adalah Jerman. Salah satu bentuk protes Jerman adalah dengan menutup mulut pada sesi foto sebelum laga.
Namun tidak semua peserta piala dunia memprotesnya. Salah satu bintang Brazil, Neymar JR, bahkan menyindir aksi timnas Jerman dengan mengatakan kalau timnya “bukan skuad jeruk makan jeruk”.
Hal itu menunjukkan jika budaya LGBT bukanlah fenomena umum yang bisa diterima oleh semua negara. Qatar sebagai penyelenggara tetap pada aturan hukum Islamnya yang melarang aktivitas LGBT di negaranya.
Contoh lagi dalam konteks kekerasan berbasis agama. Di sebagian wilayah Iran, Suriah, Afghanistan, membolehkan bertindak keras kepada orang yang melanggar aturan syariat Islam. Budaya tersebut dikonstruksi melalui pemahaman agama sehingga bertindak kekerasan atas nama agama menjadi tradisi dan budaya di sebagian wilayah negara tersebut.
Jika ajaran dan budaya tersebut dipraktikkan di Indonesia yang notebene sama-sama muslim terbanyak, maka hal itu belum tentu diperbolehkan. Mengingat bahwa konstruksi pemahaman agama di Indonesia tidak mengenal budaya kekerasan dalam memperjuangkan satu hal tertentu atas nama Islam. Tindakan kekerasan berbasis agama, karena bukan menjadi budaya masyarakat muslim Indonesia, ditolak di negara ini.
Jadi, suatu tindakan yang mungkin bersifat patologi di negara tertentu tidak perlu dipaksakan untuk diperbolehkan atas nama kebebasan berekspresi. Belum tentu tindakan A diperbolehkan di negara B, begitu sebaliknya. Semua negara memiliki aturan dan batas toleransinya sendiri-sendiri yang berasal dari kultur dari masing-masing negara. Semua aturan dan semua batas toleransi di masing-masing negara memiliki tujuan yang sama yaitu keteraturan sosial.
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin
Source link