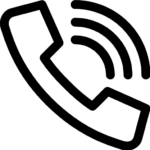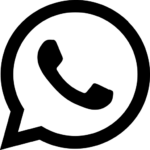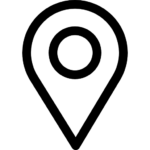Agama di Jepang (1): Shinto dan Cara Orang Jepang Memandang Agama

Ketika membicarakan bagaimana agama di mata penduduk Jepang, ada satu kutipan populer yang menyebut bahwa orang Jepang “born Shinto, marry Christian, die Buddhist”. Orang Jepang itu lahirnya Shinto, menikah dengan cara Kristen, dan meninggal dengan cara Budha. Kutipan tersebut merangkum keunikan orang Jepang dalam memandang, dan mempraktikkan agama di kehidupan sehari-hari.
Barangkali orang Jepang “sudah Shinto” sejak lahir, tapi tren gaya hidup modern mendorong banyaknya pasangan Jepang melakukan pernikahan di gereja. Sementara upacara kematian orang Jepang mengadaptasi cara Buddha. Kutipan di atas merujuk ke pemaknaan praktis kehidupan beragama orang Jepang yang lain daripada yang lain.
Praktik seperti itu jelas terdengar aneh bagi orang Indonesia – atau bagi mereka yang menganut paham monoteis – yang memeluk dan setia dengan satu agama sampai mati. Akan tapi di situlah letak keunikannya. Masyarakat Jepang memandang ‘agama’, atau ‘keyakinan’, dengan cara yang sama sekali lain. Tulisan ini akan mengungkap sedikit catatan seputar kehidupan beragama di Jepang, yang penulis rangkum dari catatan perkuliahan dengan Prof. Ken Miichi di Waseda University selama program Jenesys 2022, serta pengembangan dari beberapa bacaan tambahan.
Sekilas tentang Shinto
Yang pertama perlu dibahas dalam membincang kehidupan agama di Jepang, adalah konteks Jepang sebagai negara yang mayoritas populasinya meyakini Shinto. Shinto, dalam bahasa Jepang sendiri berarti ‘jalan Tuhan/Dewa’. Pada dasarnya Shinto berakar dari kepercayaan animisme-politeis native (asli pribumi) Jepang yang membangun identitas jepang selama berabad-abad, bahkan sejak prasejarah.
Alih-alih sebagai agama doktrin serta perangkatnya (memiliki kitab suci, nabi, atau perangkat hukum), Shinto bisa dimaknai sebagai praktik-tradisional pribumi Jepang. Shinto mencakup kepercayaan, praktik ritual, dan nilai-nilai budaya komunal yang sampai kini masih dipegang oleh warga Jepang sampai masa kini. Varian praktiknya bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada satu prinsip mendasar dari Shinto, yakni bahwa ini berbasis pada keyakinan terhadap Kami, satu entitas spiritual yang suci dan vital di alam pikir orang Jepang. Gerbang Torii yang ikonik sebagai ikon nasional Jepang, menjadi penanda signifikannya keyakinan orang Jepang terhadap adanya konsep dunia spiritual yang suci di luar dunia fana.
Keberadaan Shinto pada perkembangannya mengalami keterpengaruhan dengan agama Budha yang datang ke Jepang pada abad keenam Masehi. Sehingga masih bisa dijumpai ritual yang unik pembauran antara Shinto dan Budha. Pengaruh masuknya ajaran Budha sejak abad keenam ‘mengeraskan’ Shinto, atau dalam bahasa William C. Smith sebagai ‘reifikasi’ – proses pengentalan, pengerasan sebuah ajaran agama menjadi entitas yang baku.
Shinto yang mulanya keyakinan dan praktik tradisional yang cukup longgar dan berbeda karakter di masing-masing wilayah Jepang, menjadi sebuah ajaran yang ‘resmi’ dan ‘terinstitusi’di masyarakat. Sampai pada titik ini penulis menghindari istilah ‘Shinto-isme’ sebab Shinto memang gejala kultural yang secara organik menjadi bagian dari kepercayaan warga Jepang sejak lama, alih-alih sebagai bentukan ideologi.
Istilah ‘Shintoisme’ (Shinto yang sudah menjadi -isme atau ideologi) agaknya tepat dilekatkan pada masa Restorasi Meiji (1868-1912). Era kekuasaan yang menandai ambisi Jepang menuju peradaban modern. Mulai sejak itu, keberadaan Shinto dikeraskan dan dikembangkan menjadi instrumen penting negara dalam mengikat identitas dan membentuk loyalitas masyarakat. Di masa kekaisaran Meiji lah Shinto seperti ‘ditemukan kembali’ dan dirumuskan ulang sebagai bagian dari identitas nasional (State Shinto).
Pada masa tersebut, agama Shinto mulai dibersihkan dari pengaruh Budha yang sudah banyak mencampuri Shinto sejak abad keenam Masehi. Dalam sebuah makalahnya berjudul Reformasi dan Peran Agama di Jepang: Reformasi Budha, Rekayasa Shinto dan Peran Kristen (2015), Susy Ong, seorang ahli kebudayaan Jepang yang tinggal di Indonesia, menyebut bahwa pada masa Meiji Shinto ‘dipaksa’ menjadi agama resmi dan asli Jepang, dengan menyingkirkan unsur-unsur asing dari Budha atau agama lain. Selain itu, Shinto ditetapkan menjadi ‘asas tunggal’ negara. Banyak kuil shinto didirikan atas instruksi negara.
Kendati demikian, menurut keterangan dari Prof. Ken Miichi, kekaisaran Jepang era Meiji menolak Shinto disebut sebagai agama. Semata karena Shinto dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada “sekadar” agama dan ideologi.
“Shinto pernah menjadi asas tunggal negara, seperti Indonesia masa Orde Baru, tapi levelnya lebih dari itu. Ini karena pemerintah tidak mau menyamakan Shinto dengan agama karena menganggap Shinto posisinya di atas agama dan di atas negara.” Kata Prof. Ken Miichi dalam kuliahnya (28/01/2023).
Lahir sebagai Shinto, Menikah ala Kristen, Meninggal secara Budha
Dalam sebuah survey keagamaan di Jepang, tercatat 70% lebih orang Jepang mengaku tidak memeluk satu agama tertentu. Apalagi secara kebijakan negara, Jepang juga tidak mengakui agama resmi, atau mewajibkan penduduknya untuk memeluk agama tertentu. Tapi di sisi lain, 80% lebih orang Jepang mengaku tetap mengunjungi kuil di momen tertentu seperti Tahun Baru atau ketika memulai pekerjaan, atau berziarah ke pemakaman keluarga. Dari sini bisa dilihat, bahwa masyarakat Jepang memaknai “agama” lebih ke aspek ritual praktis, daripada doktrin keyakinan dan perangkat hukum.
Fenomena mempraktikkan ritual agama yang berbeda tercermin dalam survei statistik. Menurut data survei dari Kavanagh dan Jong (2020), dalam papernya berjudul Is Japan Religious?, terdapat 87,9 juta orang Jepang mengaku mempraktikkan Shinto dan 84,6 juta penduduk mempraktikkan ajaran Budha. Secara keseluruhan jumlah populasi data tersebut menembus angka 172 juta penduduk sementara jumlah populasi Jepang hanya sekitar 126 juta penduduk. Ini menggambarkan bahwa banyak penduduk yang mempraktikkan lebih dari satu tradisi agama di Jepang.
Meskipun dalam agama terkesan tidak religius, tapi orang Jepang masih memegang moral dan norma sosial secara konservatif. Hal ini antara lain terlihat dari statistik pernikahan.
Lazim diketahui bahwa populasi Jepang pada dekade belakangan makin menyusut. Pada tahun 2008, penduduk Jepang mencapai angka 128 juta, dan menyusut di angka 125 juta di tahun 2021. Salah satu sebab menurunnya angka fertilitas ini adalah pasangan muda di Jepang yang makin enggan memiliki anak. Akan tetapi, bukan berarti orang Jepang tidak menikah. Dalam statistik National Institute of Population and ocial Security Research pada September 2022, menunjukkan bahwa 81% laki-laki dan 84% perempuan Jepang berusia 18-34 tahun masih ingin menikah. Institusi pernikahan masih dianggap sebagai bagian penting dari keluarga untuk meneruskan trah marga keluarga.
Selain itu, meskipun negara tidak meregulasi perihal seks di luar nikah, tapi bagi masyarakat jepang, mempunyai anak di luar nikah masih menjadi hal yang sangat tabu dan menjadi beban sosial di masyarakat. Ini menjadi catatan yang unik, sebab pandangan moral orang Jepang sebenarnya masih sangat konservatif. Entah itu semata karena aspek budaya, atau dari keyakinan Shinto yang amat mengakar.
Agama Shinto sendiri juga memiliki karakter sebagai agama yang tidak ekspansif, dalam artian tidak memiliki misi penyebaran (dakwah) dan tidak pula mengkonversi pemeluk agama lain.
Kembali ke jargon “lahir Shinto, menikah ala Kristen, meninggal secara Budha”. Menurut hemat penulis, ada kesan orang Jepang memposisikan Shinto dan agama-agama lain dalam level yang berbeda. Sehingga mereka punya kecenderungan untuk ‘inklusif’ dalam hal melakukan praktik agama lain. Orang Jepang bisa dan merasa tidak berkonflik dengan keyakinan Shinto-nya saat melaksanakan praktik ritual agama lain.
Ini pula yang menjelaskan bahwa angka konversi penduduk Jepang ke agama lain bisa dibilang minim, termasuk konversi (muallaf) ke agama Islam. Mayoritas populasi Muslim di Jepang terdiri dari para pendatang/migran, dibandingkan penduduk Jepang sendiri. Untuk bahasan ini, akan penulis bahas di tulisan tersendiri. Wallahu a’lam.
(bersambung)
Tulisan ini merupakan catatan penulis dari program Jenesys 2022 dari JICE yang diadakan di Tokyo dan Hiroshima pada 24-31 Januari 2023. Sebagian besar konten tulisan ini merupakan catatan sesi kuliah Islam di Jepang yang dibawakan oleh Prof. Ken Miichi di Waseda University dalam program tersebut.
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin
Source link