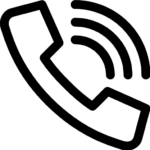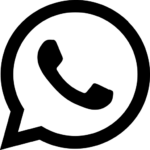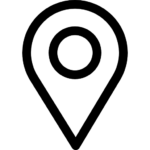Reformasi Islam: Umat Muslim Jangan Malas Berpikir!
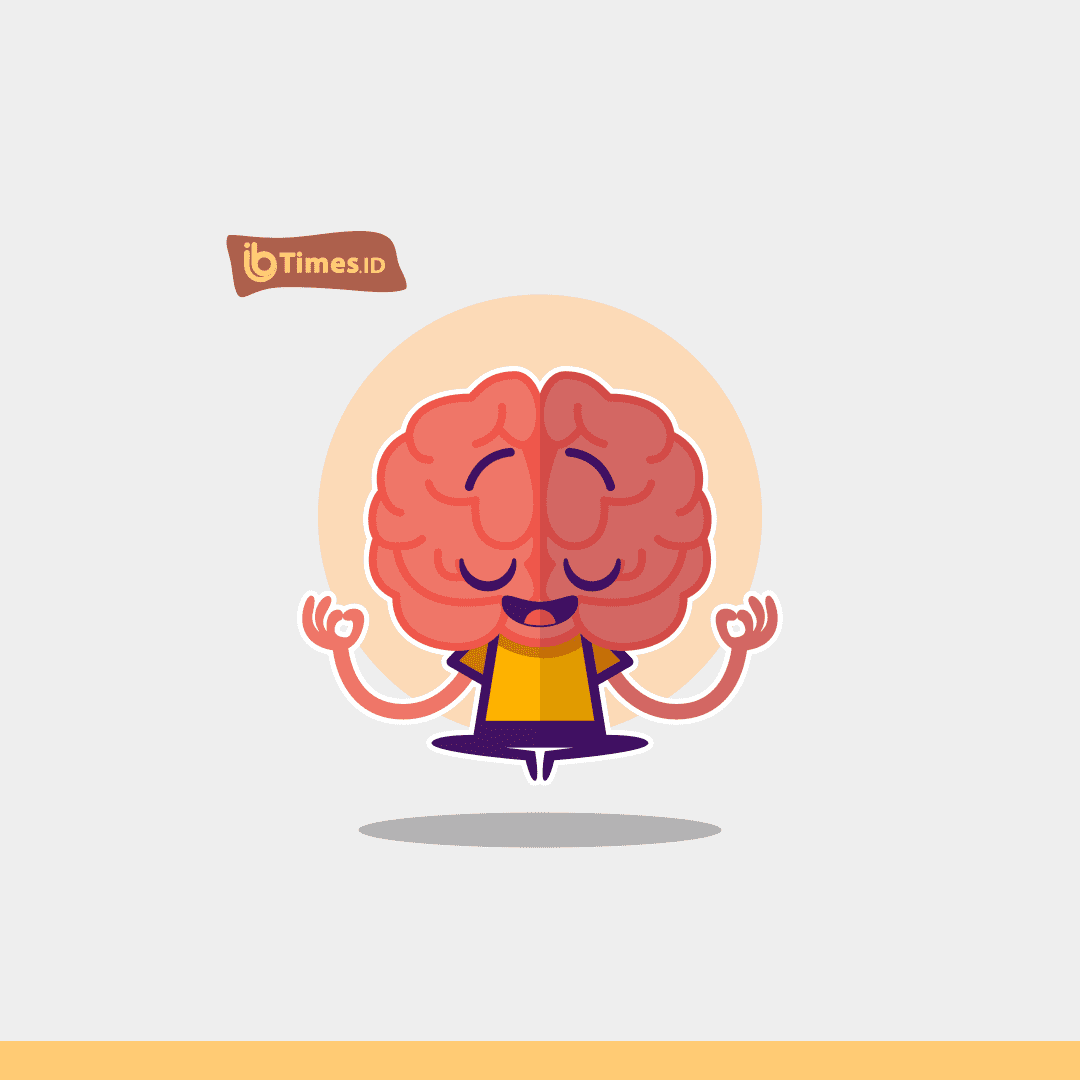
Pendahuluan
Sesekali hati saya bertanya: Apakah kita, komunitas beriman bernama Muslim, sungguh-sungguh ingin memperbaiki kondisi kehidupan? Atau: Apakah orang-orang pandai dari kalangan sarjana, pemikir, dan reformis Muslim, sungguh-sungguh ingin melihat Dunia Muslim berhasil direformasi, diubah? Sebagian besar – kalau bukan semua – perubahan signifikan dalam ajaran moral, sosial, ekonomi, dan politik kita tidak datang dari doa-doa, kesalehan ritual, revivalisme kitab suci, dan singkatnya, agama.
Semua itu adalah hasil dari proses panjang dalam pendidikan sekuler, mekanisme kerja perekonomian terkini, sistem politik dan bernegara modern, dan dari ajaran moral dan filosofis universal. Jika ada yang telah mengubah hidup kita hari ini, tidak sedikit pun kredit bisa lepas dari revolusi humanis, bukan agama.
Sebagian Muslim menangisi kematian peradaban emas Islam; satu dunia yang sudah berlalu seribuan tahun ke belakang. Mereka yang bersedih seringkali bukan pengkhotbah mimbar, pemuja sorban, atau penyandang gelar penghafal kitab suci. Tangisan itu datang dari reformis, seperti Abduh; atau fisikawan peraih Nobel, seperti Abdussalam. Bagi yang bukan reformis, apalagi fisikawan, seperti saya atau mungkin Anda, kita tidak berduka; tidak juga menganggap bahwa kewajiban Muslim bukanlah sains melainkan ritual, cadaran, atau jenggotan, seperti sangkaan banyak penikmat mimbar.
Krisis Kita, Krisis Berpikir
Matinya zaman emas Islam, dan kelahiran zaman emas humanisme dan sains modern, semata-mata merupakan bukti empiris bahwa terikat pada satu komunitas agama bukanlah sebab dan faktor bagi kehebatan dan kemajuan.
Namun, jika modernisasi tidak dilahirkan oleh “iman pada satu-satunya agama yang benar”, maka boleh jadi stagnasi dan intoleransi juga tidak dipicu oleh gairah beragama dan kesalehan bersyariat. Benarkah begitu?
Nyatanya tidak seperti itu. Indeks Islamicty yang mengukur status keislaman negara-negara dunia tiap tahun, selalu menetapkan New Zealand, Kanada, Swedia, atau Denmark, sebagai negara “Islami”. Indikator organisasi riset yang berbasis di Amerika ini adalah: Keadilan sosial-ekonomi, kebersihan birokrasi dan politik dari korupsi, hingga keamanan publik, fasilitas kesehatan, dan kemajuan bisnis; yang semuanya diyakini oleh Islamicity merupakan intisari moralitas Islam juga. Tak ada satu pun negara Muslim menduduki peringkat 40 besar.
Dan, tiap kali kita menyaksikan pemboman bunuh diri, paksaan mendirikan negara Islam, formalisasi syariat, penutupan gereja, dan pemaksaan busana agama kepada siswi sekolah, sudah niscaya para pelaku selalu bermodalkan keyakinan teguh pada satu versi fatwa yang selalu dilandasi oleh keimanan pada satu-satunya agama yang benar; atau pada satu-satunya imam yang benar.
Jika Anda dan saya termasuk kalangan Muslim yang ringan melangkah ke pos-pos vaksinasi kala pandemi Covid-19 yang lalu, ingatlah selalu jasa pendidikan sekuler yang kita terima sejak level dasar hingga universitas.
Ingat juga perubahan budaya kita menjadi budaya urban yang terorganisir oleh hasil-hasil temuan sains; sebab dahulu kala kaum nenek selalu bergantung pada doa dan mantra sewaktu cucu-cucu sakit, tetapi emak-emak kita justru mendatangi puskesmas, atau minimal posyandu, untuk mendaftarkan kita yang masih balita ke dalam program vaksinasi dan imunisasi.
Lalu ingat kembali, narasi irasional seperti apa yang menyebar kala pandemi global yang lalu terjadi. Tidak ada kontrol dari siapa pun atas ribuan penceramah yang mengajarkan jutaan orang supaya tidak percaya pada penularan virus. Percaya pada virus, disamakan dengan perbuatan syirik. Begitu pula percaya pada vaksinnya, atau sekadar pemakaian masker.
Jelas, atmosfer budaya dalam pada umumnya Dunia Muslim masih terkontaminasi polusi krisis berpikir. Kita tidak lagi merasakan mengalirnya air perubahan yang segar dari cara berpikir kitab-suci-sentris, hadis-sentris, atau ijma’-ulama-sentris. Percayalah, pengakuan atas hak-hak asasi manusia, atau inisiatif global pencegahan pandemi secara saintifik, tidak pernah timbul dari investigasi atas huruf-huruf kitab suci; melainkan justru dari akal sehat dan hati nurani manusia terdidik.
Reformasi Berpikir Belum Berakhir
Satu di antara benda penting yang pernah mampir ke ingatan kita sebagai Muslim haruslah Islamic Reform (reformasi Islam). Terutama setelah terjadi modernisasi di Dunia Muslim sejak abad 19 hingga sekarang, integrasi psikologis kaum Muslim ke dalam modernitas banyak berhutang pada kecerdasan insan-insan reformis, seperti Tahtawi, Ali Abd al-Raziq, Dahlan, atau Harun Nasution.
Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Islamic Reform mereka begitu impresif sebagai bahan studi di tangan kelas akademia, hanya saja tidak pernah benar-benar mengubah dominasi konservatisme dan formalisme di alam pikiran kaum Muslim, atau dominasi otoritas institusi ulama sebagai pemutus kebenaran.
Mu’tazilisme Nasution adalah contoh terbaik. Terbaik karena tepat sekali Nasution dalam membuktikan krisis akut yang tidak pernah terobati dalam diri Muslim, yaitu sektarianisme dan dogmatisme yang dua-duanya tidak rasional sama sekali.
Tawaran revitalisasi Mu’tazilisme olehnya membentur respons “astaghfirullah”, “innalillah”, hingga “na’udzubillah”. Sektarianisme di Dunia Muslim itu nyata; kita bisa menuding A-B-C-D kepada “sekte” di luar “sekte ahli-surga” milik kita. Dogmatisme itu juga nyata; kita menutup pintu untuk setiap usaha nalar dalam mengkritik dogma usang yang kita bela. Jelas, Mu’tazilah yang amat nalar-sentris dalam beragama adalah duri paling mengganggu bagi spirit sektarian dan dogmatik dalam Sunni.
Di samping Nasution, contoh terbaik kedua adalah sekularisasi Cak Nur pada 1970, dan pluralisme (juga) Cak Nur pada 1992.
Kini orang ramai berbicara soal gagalnya tesis sekularisme, sambil pura-pura lupa bahwa sebagian besar negara-bangsa dipimpin oleh orang yang dipilih dengan mekanisme demokrasi, diatur oleh regulasi buatan parlemen, bersengketa di depan majelis hakim hukum positif, dan bergantung secara ekonomi dan ilmiah pada institusi sekuler bernama pasar dan universitas.
Tawaran sekularisasi Cak Nur – yakni tidak mensakralkan apa pun selain Tuhan saja – membentur tembok post-modernisme dan Islamisasi pengetahuan.
Ksatria post-modernis beranggapan bahwa adalah hak setiap budaya dan keyakinan untuk mensakralkan apa saja semau mereka. Bagi mereka, yakni post-modernis, tidak ada nalar objektif dan kebenaran universal; semua hal itu subjektif; tidak ada kelebihan sains modern atas budaya tradisional.
Islamisasi pengetahuan lain lagi. Bagi mereka, semua segi aktivitas manusia harus di-Islam-kan, karena tidak ada paradigma yang benar kecuali setelah mengakui rukun-rukun kepercayaan Islam.
Bisa ditebak ke mana proyek Islamisasi akan bermuara: Penguatan sentimen identitas dalam Islam politik, retorika ekonomi Islam demi menggaet nasabah-nasabah saleh, branding busana syar’i yang memecah-belah publik menjadi Muslim yang syar’i dan tidak syar’i, hingga “kedokteran Islam” yang entah di mana Islaminya kecuali pada nama “rumah sakit Islam” atau suster berjilbab.
Semua itu, bersama dengan ancaman atas pluralisme beragama, membuktikan betapa tepatnya Islamic Reform Cak Nur dalam mengungkap penyakit kronis Muslim Indonesia, yaitu eksklusivisme dan intoleransi.
Namun, tidak Mu’tazilisme Nasution, tidak pula sekularisasi Cak Nur; kedua-duanya pernah lepas landas tapi jelas tidak bisa dikatakan sudah dapat beristirahat. Islamic Reform belum selesai. Muslim selalu perlu penyegaran pikiran kembali, sampai ketika agama tidak lagi dilihat sebagai “suku-suku” yang saling bertikai, dan ketika nalar-sentris menggantikan hadis/kitab-suci-sentris.
Kesimpulan
Sejak dicetuskan oleh sejumlah reformis, Islamic Reform tidak pernah bisa berdiri sendiri. Tidak ada perubahan/perbaikan yang benar-benar bisa terpenuhi apabila dilandasi moral “setengah hati”. Sebagai pengingat bagi kita, tidak semua reformasi Islam berjalan di jalur yang tepat. Islamic Reform bukanlah sekadar reinterpretasi atas teks suci agar harmonis dengan perubahan terkini. Semestinya ia merupakan kesadaran yang disengaja bahwa hanya dengan nalar-lah manusia mampu memisahkan yang benar dari yang salah. Jika nalar menjadi “bahasa” kita, maka kita berbicara sebagai warga dunia, dan melihat kebenaran sebagai milik bersama.
Editor: Soleh
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin
Source link